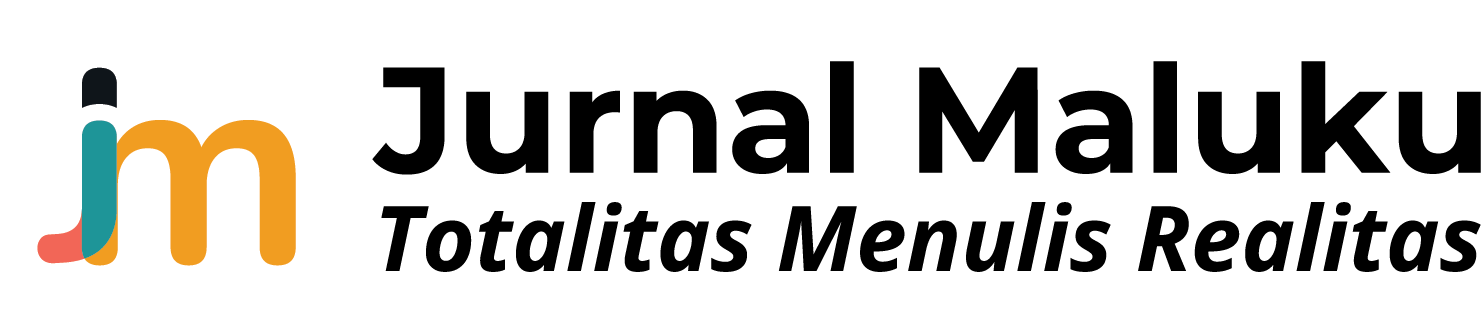Program dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tampak massif pada beberapa tahun terakhir dengan Program Dana Desa dan upaya pemberdayaan masyarakat desa yang gencar dilakukan. Kendati demikian, dalam praktiknya program dan kebijakan pemerintah ini tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun dimensi kehidupan lain seperti kesehatan, pendidikan dsb. Salah satu faktor yang tampaknya memiliki peranan besar atas kebuntuan ini adalah tidak tepatnya program dan kebijakan pemerintah.
Tidak tepatnya program dan kebijakan yang dimaksudkan dikarenakan kurangnya ruang untuk mewadahi basis kultural dan struktur sosial masyarakat dalam pembangunan. Basis kultural dan sturktur sosial masyarakat desa yang sangat particular seringkali diseragamkan sehingga pembangunan menjadi semakin mengakar dalam kultur masyarakat. Imbas dari hal ini, program dan kebijakan untuk kesejateraan tidak pernah bertahan lama (temporer) dan berciri karitif. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan sering tidak menyertakan aspek perubahan sosial dan kultural masyarakat dan aspek pembangunan berkelanjutan (Susteinable development).
Paradigma pembangunan tersebut semakin dipertegas dengan penggunaan pendekatan Problem Solving (selanjutnya disingkat PS). Kecenderungan PS melihat komunitas sebagai organisasi yang bermasalah. Tendensi ini membuat masyarakat desa dilihat sebagai sebuah komunitas yang memiliki masalah untuk mencapai standar kesejahteraan tertentu. Stigmatisasi sebagai “masyarakat yang terbelakang” atau “masyarakat tertinggal” memperkuat anggapan bahwa paradigma pembangunan menggunakan pendekatan PS dalam perencanaan dan implementasinya. Berbeda dari kecenderungan tersebut, pendekatan Appreciative Inquriy yang menekankan potensi dan keungulan dapat lebih inklusif terhadap dimensi sosial, kultural bahkan spiritual masyarakat desa.
Pembangunan dan stigmatisasi masyarakat desa
Dalam praktiknya, pembangunan di Indonesia memang belum benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa. Sejak periode 2000, tercatat cukup banyak kasus penolakan pembangunan antara masyarakat desa dengan perusahaan. Beberapa kasus di Maluku misalnya melahirkan gerakan massa dalam jumlah yang cukup banyak. Salah satu upaya penolakan yang berhasil adalah yang dilakukan gerakan #savearu pada tahun 2013 untuk menolak pembukaan lahan besar-besaran di kepulauan Aru. Terakhir bangkitnya perlawanan masyarakat adat Sabuai di Seram Bagian Timur karena hutan mereka menjadi korban eksploitasi brutal.
Michael Dove (1984, 55) dalam bukunya Peranan kebudayaan tradisional dalam pembangunan mengatakan bahwa salah satu penyebab tersendatnya kehidupan masyarakat desa adalah konsep pembangunan di Indonesia yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di Indonesia dipahami sebagai sebuah perubahan untuk mengejar keuntungan ekonomi/profit, sehingga apa saja yang berlawanan dengan orientasi itu, akan dianggap sebagai sebuah keterbelakangan.
Kehidupan masyarakat desa yang seringkali menekankan harmonisasi dan tidak eksplosif dalam memanfaatkan alam justru sering dinilai sebagai sebuah ketertinggalan jika dibandingkan dengan ambisi negara mengejar keuntungan ekonomi. Oleh sebab itu, budaya dan dimensi sosial masyarakat desa yang seringkali dianggap berlawanan dengan modernitas akan dinilai sebagai penghalang bagi pembangunan.
Di Maluku, proses stigmatisasi masyarakat desa sebagai yang “terbelakang” atau “tertinggal” pernah menimpa orang-orang Huaulu dan Masyarakat Pegunungan Taniwel. Pada tahun 1991, orang-orang Huaulu yang bermukim di Sekinama dipindahkan oleh pemerintah ke Wahai dengan alasan pemukiman baru. Demikian halnya dengan orang-orang Lohiasapalewa, Neniari, Riring, Rumahsoal, Buria dan Laturake. Pemerintah lewat Departemen Sosial saat itu melaksanakan proyek “pembinaan suku-suku terasing” yang memaksa agar masyarakat lokal yang hidup di pengunungan dipindahkan ke wilayah pesisir. Alasannya adalah agar masyarakat tersebut tidak lagi terbelakang dan lebih maju.
Orang-orang Huaulu yang menolak pindah tidak hanya dilabeli sebagai orang orang terbelakang tetapi juga dilabeli sebagai pendukung RMS. Demikianpun dengan orang-orang gunung di pegunungan Taniwel yang di cap orang terbelakang.
Khusus bagi orang-orang Huaulu, Nus Ukru dalam laporannya menyebutkan bahwa proses pemindahan orang orang Huaulu dari Sekinama ke Wahai sejatinya hanya menjadi pintu masuk bagi PT. Bharata Jaya yang mendapat ijin konsesi untuk menebang kayu yang awalnya adalah hutan adat milik orang orang Huaulu. (Nus Ukru, “Orang Huaulu Pencinta Damai yang terancam punah”, dalam R.Topatimasang. 2016. 144)
Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam praktiknya tidak menunjukan aspek kesetaraan (equality). Masyarakat desa dengan stigmatisasi sebagai yang terbelakang dan tertinggal “dipaksa” untuk menerima proyek pembangunan yang digagas oleh pemerintah. Dari perspektif ini, program yang dibawa pemerintah dianggap sebagai sebuah bantuan untuk mengeluarkan masyarakat desa dari jerat ketertinggalan dan keterbelakangannya. Paradigma ini senantiasa menempatkan masyarakat desa sebagai pihak yang tidak memiliki daya maupun pengetahuan untuk mendapatkan standar kehidupan yang lebih baik. Masyarakat desa akan selalu membutuhkan bantuan pihak lain seperti negara ataupun korporasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Akan tetapi, narasi ini justru berlawanan dengan praktik-praktik yang dapat ditemukan di lapangan. Alih alih mensejahterahkan masyarakat, konsep pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan pemerintah justru seringkali menunjukan kolaborasi negara/pemerintah dengan koorporasi demi kepentingan kelompok tertentu. Masyarakat desa yang tidak secara serius diberdayakan oleh negara justru semakin tertinggal akibat ekspansi korporasi di wilayah adat mereka.
Pembangunan dan pengabaian terhadap dimensi sosio-kultural
Ketertinggalan masyarakat desa dalam pembangunan yang pesat menjadi sebuah ironi. Pasalnya eksploitasi sumber daya alam di pedesaan semakin meningkat setiap tahunnya. Khusus wilayah Maluku maupun Maluku Utara, sektor ekstraktif seperti pertambangan menjadi salah satu sektor yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya tersebut juga memicu banyak pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah maupun perusahaan. Misalnya pada tahun 2017, perlawanan masyarakat desa Tolong, Kepuluan Taliabu pada melawan PT. Adidaya Tangguh yang mendapatkan ijin konsesi dari pemerintah kabupaten, menambang bijih besi dikawasan tersebut. Kendati kedatangan perusahaan memberi sedikit ruang untuk menyerap pekerja, mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani justru merasa terpuruk dengan kehadiran perusahaan. (Roem Topatimasang. 2016. 61-62)
Pola pembangunan semacam ini, berdiri di atas asumsi bahwa masyarakat desa pada dirinya sendiri tidak memiliki potensi.
Masyarakat desa beserta kehidupan sosialnya adalah kelompok yang memiliki masalah dengan tingkat kesejahteraan. Satu-satunya solusi untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat adalah Sumber Daya Alam (SDA). Desa yang cenderung memilki kelimpahan SDA akan lebih mudah mendapatkan perhatian pemerintah, ketimbang desa yang kurang memiliki kekayaan SDA. Meskipun sumber daya lain seperti sumber daya manusia mungkin lebih memadai, tetapi dalam paradigma pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, kekayaan SDA tampak lebih menjanjikan.
Kendati demikian, dalam pengelolaan SDA tersebut, masyarakat desa seringkali hanya menjadi “pemeran pembantu” atau bahkan “penonton” di daerahnya sendiri. Masyarakat desa yang tidak memiliki kultur, pengetahuan bahkan peralatan untuk pengelolaan SDA yang eksplosif dan modern seringkali hanya menjadi pegawai rendahan ataupun buruh pada perusahan yang mengelola SDA di wilayahnya sendiri. Seperti yang dialami orang orang Tobelo Luar pada tahun 1970-an, yang hanya menjadi buruh kasar pasca masuknya perusahan tambang. Orang orang Tobelo menjadi pemeran pembantu karena secara kultural memiliki kehidupan yang berorientasi pada meramu, berburu dan berladang.
Orang-orang Riring, Rumah Soal dan sekitarnya dipegunungan Taniwel pernah dilarang untuk menanam Bawang Putih, Bawang Merah, Kentang, Sayur Kol dan lain-lain dengan alasan tidak sesuai standar pasar. Padahal, tanaman yang mereka hasilkan bebas dari unsur kimia berupa pupuk dan sebagainya. Dalam waktu yang panjang, mereka diabaikan hidup sebagai masyarakat peramu, berburu dan berladang yang hidup dengan kemiskinan.
Ada juga kisah lain, seperti yang dipaparkan Tania Murray Li dalam bukunya Kisah dari Kebun Terakhir, (2014; 287) Li menemukan fakta bahwa orang orang Lauje di perbukitan khususnya para petani yang kehilangan akses pada tanahnya adalah kelompok masyarakat yang paling menyedihkan. Para petani yang gagal itu diharapkan untuk memasuki jalur transisi ke bidang pekerjaan lain, di tempat lain tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi. Rencana pembangunan menurut Li tidak berpihak kepada mereka yang tidak memiliki tanah sedangkan lapangan kerja dengan upah yang layak pun tidak tersedia. Bagi Li, keadaan ini adalah sebuah tantangan politik untuk mengatasi situasi orang yang tanpa tanah, tanpa kerja, tanpa jaminan sosial dan tanpa sekutu.
Kehidupan yang terancam tidak hanya soal pemenuhan pangan, tetapi dampak buruk pasca aktivitas perusahaan seperti kerusakan ekologis (penurunan kualitas udara/air/tanah) hingga degradasi kultural dan sosial juga lebih berimbas kepada kehidupan masyarakat desa/negeri. Kerusakan ekologis dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat, tetapi pada sisi lain seperti tatanan sosial dan budaya masyarakat yang sejatinya saling berkelindan satu sama lain juga terkisis karena pembangunan. Seperti pada kasus orang Huaulu, pembangunan yang mengorbankan hutan-hutan sagu turut berimbas pada kohesi sosial orang Huaulu. Kebersamaan masyarakat untuk secara bergotong royong menokok sagu telah hilang seiring dengan hilangnya hutan-hutan sagu mereka.
Kecenderungan ini menunjukan bahwa dalam paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak hanya memahami masyarakat desa sebagai sebuah komunitas yang bermasalah dengan tingkat kesejahteraan. Tetapi paradigma tersebut juga sangat abai dengan basis kultural dan sosial masyarakat. Seperti hutan sagu yang menjadi tempat terjalinnya kohesi sosial bagi orang Huaulu.
Berbagai fenomena tersebut, menampilkan ketidakpedulian paradigma pembangunan terhadap dimensi sosio-kultural masyarakat. Sebagai gantinya, paradigma pembangunan yang digagas negara itu justru berfokus pada upaya pengelolaan SDA yang harus efisien dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar mungkin. Dengan orientasi ini tidak mengherankan jika dimensi sosial dan kultural masyarakat yang dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi menjadi sangat diabaikan bahkan cenderung dihilangkan begitu saja.
Appreciative inquiry dan pembangunan berbasis potensi
Paradigma pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi tampak semakin menegaskan ketidakberdayaan masyarakat desa ketika pendekatan yang digunakan adalah problem solving (PS). Dalam pendekatan PS, komunitas masyarakat termasuk masyarakat desa akan dipahami sebagai sebuah komunitas yang memiliki masalah untuk mencapai idealisme tertentu (kesejahteraan). Tendensi yang muncul dari pendekatan ini adalah sebuah komunitas yang memiliki masalah, kesulitan untuk menemukan solusi sehingga membutuhkan pihak eksternal untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. (Silvia Fanggidae. 2011) Masyarakat dan kehidupannya (sosio-kultural) tidak dilihat sebagai sebuah potensi melainkan sebagai sebuah masalah bagi pertumbuhan ekonomi.
Pada titik ini, paradigma pembangunan dan tendensi yang muncul dari pendekatan PS dapat membuat masyarakat desa terjerembab dalam jurang ketidakberdayaan yang tak berujung. Dimensi keberlanjutan (sustainable) dari pembangunan mustahil untuk dikembangkan karena dengan PS, sebuah komunitas akan dianggap selalu membutuhkan pihak lain yang lebih superior sehingga sifat dependensi dari sebuah komunitas akan terpelihara dan bahkan membudaya.
Berbeda PS dengan Appreciative inqury (selanjutnya disebut AI) menawarkan sebuah pendekatan yang berbeda. AI lebih berorientasi pada pengembangan potensi ketimbang berusaha menjawab permasalahan sebuah komunitas. Pendekatan ini digagas oleh David Cooperrinder dan Suresh Srivastya yang menangani pengembangan organisasi di Cleveland Clinic. Di klinik tersebut, Cooperrider dan Srivastya mengubah hal yang sekian lama dilakukan para pengembang di klinik tersebut, dari upaya menyelidiki apa yang tidak berfungsi dalam organisasi kepada menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi pada efektivitas organisasi. Penyelidikan tersebut berkontribusi positif terhadap efektivitas organisasi berhasil mendorong keterlibatan antusias seluruh anggota organisasi untuk membicarakan kisah-kisah keberhasilan kisah-kisah keberhasilan.
Pendekatan AI memiliki beberapa siklus yang berbeda dengan pendekatan PS antara lain pertama adalah mengapresiasi “apa yang ada”atau (discovery), kedua Imajinasi “apa yang ada”(dream), ketiga menentukan “apa yang harus” (destiny) keempat, menyusun “apa yang didapat” (design). Keempat siklus ini kemudian termanifestasi dalam analisis SOAR (Stregth, Opportunities, Aspirations, Results). SOAR memiliki semangat yang sama dengan AI karena berorientasi pada penentuan aset/potensi terbesar, penentuan peluang, penentuan tujuan, dan penentuan capaian hasil yang terukur (Kharis Ragil Triyanto, Dwi Putra Darmawan, I Putu Gede Sukaatmadja. 2016 ; 122). Pendekatan AI yang terejewantahkan dalam analisis SOAR benar-benar mendorong masyarakat untuk memperhitungkan peluang dan kekuatannya untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga masyarakat tidak lagi melihat dirinya sebagai kelompok tanpa daya dan tanpa potensi.
Dengan pendekatan AI dan analisis SOAR, potensi masyarakat desa bukan hanya sumber daya alamnya, tetapi lebih daripada itu, dengan pendekatan AI potensi masyarakat juga adalah kultur, kehidupan sosial, tradisi, bahkan kearifan lokal sebagai sebuah potensi dan peluang yang dapat dikembangkan. Hal ini dapat dimungkinkan karena dalam pendekatan AI, masyarakat sendiri yang menentukan mana yang menjadi potensi dan keunggulannya dan bukan pihak luar. Tentu saja dengan persepsi yang tepat, keungulan dan potensi tidak hanya diarahkan kepada SDA tetapi juga kultur dan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.
Dalam kesadaran itu maka pembangunan tidak harus memisahkan alam dari kehidupan masyarakat seperti yang dipraktikan selama ini, melainkan melihat alam dan kehidupan sosial budaya masyarakat sebagai aspek yang berkelindan satu sama lain. Masyarakat mengenali bahkan menentukan sendiri apa yang menjadi potensi, peluang dan kisah-kisah sukses. Dengan adanya AI, diharapkan pembangunan mengintegrasikan masyarakat desa di dalamnya sehingga tidak lagi menjadi “penonton” dari pembangunan.
Partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan
Pengunaan pendekatan AI dalam pembangunan komunitas masyarakat bukan lagi sebuah hal baru di Indonesia, beberapa literatur dan penelitian menunjukan bagaimana pendekatan AI sangat mungkin untuk diaplikasikan dalam membangun masyarakat baik di kota maupun di pedesaan. Beberapa desa dan komunitas telah menggubah pola perencanaan komunitas dari PS kepada AI. Salah satu contoh penggunaan AI bagi pengembangan masyarakat ditunjukan oleh Anisatul Auliya yang menegaskan bahwa pendekatan AI dan SOAR dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata di kota Depok.
Penelitian Auliya menunjukan bahwa rencana pengembangan wisata di kota depok dengan menggunakan analisis SOAR menunjukan banyak aspek kekuatan internal yang selama ini kurang disadari. Kekuatan budaya dan tradisi masyarakat sekitar lokasi wisata yang abai dalam pendekatan PS, dalam AI dan SOAR justru dilihat sebagai peluang dan potensi bagi pengembangan pariwisata. Tugas pengembangan pariwisata dengan analisis SOAR menjadikan masyarakat sebagai kelompok yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan tempat wisata. Hal ini tidak hanya berimbas pada meningkatnya pendapatan tetapi juga terjaganya budaya dan tradisi masyarakat di sekitar tempat wisata. Penerapan AI tanpa disadari telah dilakukan oleh masyarakat Desa Welora di MBD dengan kisah sukses mereka membangun desanya menjadi destinasi wisata bertaraf internasional.
Jika dalam sektor tambang maupun perkebunan skala besar, masyarakat desa hanya menjadi penonton maupun pemain kelas bawah karena tidak memiliki kultur dan pengetahuan tertentu, maka dalam sektor pariwisata, kultur dan pengetahuan asli masyarakat justru menjadi potensi yang dapat dijual kepada penikmat destinasi wisata selain juga keindahan dan pesona alamnya. Kolaborasi antara keindahan alam dan kehidupan masyarakat lokal akan menjadikan pengalaman berwisata menjadi sangat otentik dan berbeda.
Perubahan pola konsumsi dari keinginan untuk memiliki barang atau properti kepada keinginan untuk memiliki pengalaman sedang terjadi saat ini. Khusus untuk generasi milenial, pola konsumsi tidak lagi berorientasi kepada kepemilikan rumah, kendaraan dll tetapi bergeser kepada orientasi untuk “membeli” pengalaman. Hal ini terlihat dari membudayanya traveling atau backpacker di kalangan anak muda. Genarasi milenial lebih memilih untuk mengunjungi sebuah tempat yang sedang viral ketimbang menabung untuk membeli rumah (Uslarika Hida Rahma, Cholichul Hadi, Ilham Nur Alfian, 2021).
Perubahan pola konsumsi ini dapat menjadi peluang bagi pengembangan pariwisata di desa sebagai salah satu alternatif selain perkebunan dan pertambangan. Dua wujud yang penting diperhatikan adalah porsi pengelolaan yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah serta dimensi keberlanjutan dari pengelolaan tersebut. Pengelolaan yang seimbang sangat dibutuhkan agar bidang pariwisata tidak mengulangi kesalahan sektor tambang yang sering menjadikan masyarakat desa sebagai penonton. Pada sisi lain, keberlanjutan dalam kerangka ramah lingkungan juga penting untuk diperhatikan, agar pengelolaan tempat pariwisata tidak mematikan mata pencaharian warga yang lain seperti bertani, berladang dll.
Dalam konteks Maluku, pengembangan pariwisata sebagai alternatif dari sektor pertambangan dan perkebunan monokultur. Maluku menyimpan banyak potensi destinasi wisata yang belum dikelola secara masksimal. Mulai dari Maluku Tengah, Maluku Tenggara hingga Maluku Barat Daya, memiliki potensi pariwisata ramah lingkungan yang sangat menjanjikan. Kombinasi keindahan wilayah pegunungan dan pesisir pantai menjadi anugerah yang harus dimaksimalkan lewat sektor pariwisata. Terutama untuk menjawab perubahan sosial di kalangan generasi millennial yang lebih memilih berwisata ketimbang berinvestasi.
Sebuah kebanggan yang perlu diingat pula bahwa dalam Ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) Award yang dilakukan pada bulan Mei 2021 lalu di Labuan Bajo (NTT), Propinsi Maluku justru menunjukakan prestasinya pada level nasional dengan mendapatkan 6 juara nasional pada 6 kategori berbeda. WELORA, KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, meraih tempat pertama untuk kategori Destinasi Wisata Baru Terpopuler. RUMAH POHON WAAI, MALUKU TENGAH meraih tempat pertama pada kategori Destinasi Kreatif Terpopuler, AMBON CITY OF MUSIC menempati posisi ke-3 untuk kategori Brand pariwisata, KAIN TENUN TANIMBAR juga menempati tempat ke-2 untuk kategori Cinderamata Terpopuler, TARAWESI MOTOKROS, Kabupaten Buru, menempati tempat ke-3 pada kategori Wisata Olahraga dan Petualangan Terpopuler, serta Instagram EXOTIC MALUKU TOURISM milik Dinas Pariwisata Provinsi Maluku meraih juara ke-3 untuk kategori Promosi Digital Pariwisata. Prestasi ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan sebagai modal bangkitnya pariwisata di Maluku, yang kaya akan destinasi wisata, kuliner, dan budaya yang harus diekspos.
Kendati cukup banyak tantangan dan keterbatasan seperti akses transportasi maupun akomodasi, penting bagi masyarakat menganalisis semua peluang dan kekuatan seperti dalam analisis SOAR agar upaya pembangunan sektor pariwisata tersebut dapat dimulai oleh masyarakat. Terlebih program dana desa yang semakin merata berbagai wilayah dapat menjadi peluang yang menjanjikan. Mengingat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten.
Selain sektor pariwisata, sektor seperti ekonomi kreatif dan industri rumahan pun dapat menjadi sebuah peluang bagi pembangunan masyarakat. Masyarakat di Pulau Saparua dengan berbagai kuliner, kerajinan tangan, yang adalah produk budaya dan tradisi masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah peluang. Pembentukan sentra-sentra ekonomi yang mengedepankan komoditi asli masyarakat perlu digagas agar ketergantungan antara masyarakat desa dan kondisi ekonomi perkotaan dapat terjembatani dengan baik. Selain metode konservatif seperti sentra ekonomi, penting untuk melihat peluang pemasaran atau marketing di era digital yang memungkinkan jarak antara pembeli dan penjual bukan lagi sebuah masalah.
Pendekatan AI dan analisis SOAR memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Implementasi yang jelas dan transparan seperti dalam pengelolaan sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif dapat menjadi opsi alternatif bagi pemerintah yang cenderung mengutamakan sektor ekstraktif seperti pertambangan maupun perkebunan monokultur. Pembangunan dalam sifatnya yang berkelanjutan juga penting untuk memikirkan ketahanan sosial masyarakat, terpeliharanya nilai dan kearifan lokal masyarakat bahkan kelestarian lingkungan hidup sebagai orientasinya.