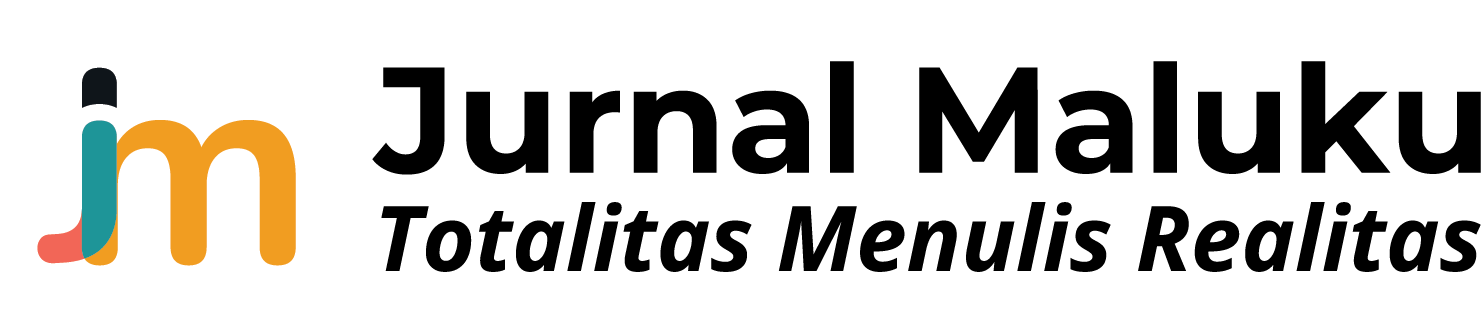Masyarakat Maluku pernah “dijajah” 350 tahun. Banyak hal terjadi dalam masa itu, termasuk konflik dan pertikaian. Tetapi di Maluku terdapat satu artefak budaya yang unik, yakni tradisi pela gandong yang merata di hampir semua wilayah. Namun pernahkah kita berpikir, bahwa relasi itu tumbuh antara lain di tengah era ‘350 tahun kolonial’? Ada banyak persoalan di sana.
Lantas, tahun 1945, “….atas berkat Tuhan yang mahakuasa…”, kita merdeka. Kita menjadi satu bangsa dengan berbagai beban-beban masa lalu yang tidak sepenuhnya terselesaikan. Termasuk persoalan batas tanah, persoalan antara ‘yang asli’ versus ‘pendatang’. Itu kabut yang membayang kehidupan kita di masa kini.
Tahun 1999 kita alami bencana sosial yang begitu kelam. Tetapi kita bersyukur bahwa karena RohNya, kita dituntun untuk ‘mengakhiri keterlibatan’ dalam konflik. Kita tidak mau lagi diprovokasi, diadudomba, karena kita ingin perdamaian. Perdamaian adalah mimpi indah, kehendak Tuhan di tengah bencana.
Tetapi ketika damai itu telah datang, jangan lupa, ada banyak beban-beban yang harus diselesaikan. Kita harus semakin rendah hati satu terhadap yang lain, peran agama-agama harus semakin terarah pada teologi yang menghargai perbedaan. Kita harus kembangkan politik lokal yang dibangun atas dasar persaudaraan di tengah perbedaan. Keadilan dan kesejahteraan harus semakin merata dan adil dalam berbagai aspek.
Agama-agama harus mampu mentransformasi tradisi pela gandong dalam teologi kontekstualnya, pela gandong harus ditransformasi sebagai acuan etik dalam ruang publik Maluku, termasuk praktek kekuasaan dan politik lokal.
Kesadaran saya sebagai orang Waai terhadap saudara pela Wakal, Morela yang Islam, tetapi juga yang turut mewarisi tradisi persaudaraan Amarima, menjadi dasar etik saya menghargai seluruh umat Islam di dunia. Ketika saya berjumpa dengan basudara dari Hualoy, Latu, pun Buton, Bugis, Makasar, Jawa yang beragama Islam, saya menerima mereka sebagai saudara karena saya punya saudara Wakal, Morela dan Amarima.
Begitu pun sebaliknya.
Itu membuat pela gandong dihidupi sebagai sebuah kesadaran teologi dan moral, tidak menjadi instrumen untuk menguasai yang lain, tetapi (pela gandong) menjadi instrumen menciptakan perdamaian dalam oikos/dunia yang diberikan Tuhan.
Jadi perang, konflik dan kekerasan itu tragedi, tetapi perdamaian itu sebuah perjuangan, bukan hanya kata-kata, slogan, tetapi kerja nyata, pikiran dan tindakan. Damai itu telah datang, maka dalam damai itu, dengan spirit pela gandong yang transformatif, kita selesaikan semua persoalan-persoalan kita.
Sesudah itu, kita sujud bersyukur pada Tuhan. Tuhan pasti terima dan sempurnakan doa kita, karena kita telah tulus berpikir dan bertindak.
Salam Damai,
Penulis: Pdt. Daniel Wattimanela